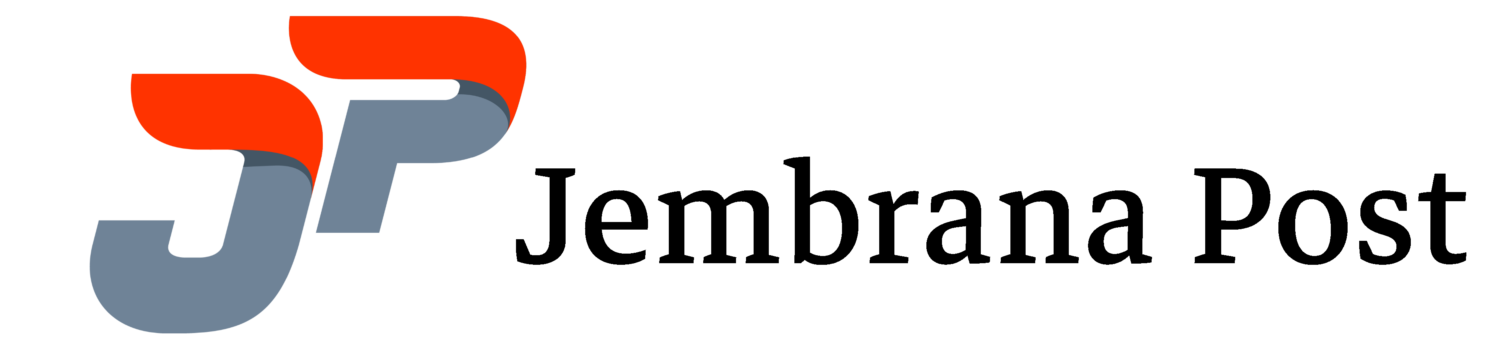Dimana-mana, saya dan mungkin Anda melihat orang-orang yang tampak asyik dengan gawai. Entah melihat media sosial, menonton video, bermain game, atau terlibat dalam percakapan virtual. Bahkan hingga tak peduli dengan lingkungan sekitar atau lawan bicara, jika mereka sedang berkumpul bersama.
Fenomena ini mengingatkan saya pada Clifford Geertz, antropolog kawakan yang puluhan tahun silam meneliti dan menulis tentang sabung ayam di Bali. Ia menyebut aktivitas itu sebagai “Deep Play” atau “Permainan Mendalam”.
Sabung ayam, menurutnya tak sekedar pertarungan ayam jago tapi juga soal status, harga diri, bahkan keinginan berkuasa yang tak tampak dari pelaku tradisi tersebut. Pada titik ini, tak berlebihan jika kita bandingkan dengan kebiasaan”bermain gawai” pada masyarakat di masa sekarang.
Gawai kini menjadi barang wajib yang dimiliki, jika ingin disebut manusia modern. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2019-2020 sebanyak 196.71 juta jiwa atau 73,7 % dari 266.91 juta jiwa, total populasi penduduk Indonesia. Apa yang membuat masyarakat kita begitu lekat pada internet? Jawaban atas pertanyaan ini tentu beragam.
Obyek permainan bisa berlainan, jika dulu misalnya ayam jago kini berubah ke sesuatu yang lain, gawai. Seorang musisi terkenal menciptakan lagu bagus tentang ini. Kecanduan internet digambarkannya dengan satir (bahkan) di tempat ibadah kita sibuk dengan gawai. Internet disebutnya sebagai Dajjal, sosok yang kerap disebut dalam kitab suci sebuah agama.
Teknologi memang bagai mata pisau. Kini tergantung kita, larut dalam permainan atau menjaga jarak dengannya. Perlu interpretasi akan hal ini. Apakah kebiasaan bermain gawai hanyalah bentuk budaya baru atau ancaman terhadap peradaban manusia, karena kecanduan gawai dan internet membuat komunikasi di kehidupan nyata berkurang atau bahkan bisa hilang sama sekali.
Ceracau
Di sisi lain, media sosial, salah satu fitur dalam gawai kini memang menjadi permainan yang mengasyikkan bagi kebanyakan orang, termasuk para penulis. Menjadi wadah ekspresi tempat berbagi pemikiran dan karya, melalui tulisan pendek dan panjang atau sekadar status yang hanya terdiri dari beberapa kata.
Ruang interaktif yang menjadi ciri khas media ini membuat setiap tulisan bisa dikomentari pengguna lain menghadirkan suasana yang hampir mirip dengan kehidupan nyata. Hiperrealitas, meminjam istilah seorang pemikir.
Saya perhatikan, beberapa kawan penulis yang aktif di media sosial juga aktif menghasilkan karya misalkan menulis buku. Awalnya saya berasumsi media sosial menjadi godaan besar penulis, karena bisa menyita waktu produktif dengan saling berbalas komentar atau terlibat dalam diskusi dan obrolan tentang sebuah isu atau fenomena yang hangat dibicarakan.
Bagi penulis yang jeli dan cerdas, media sosial bisa jadi menjadi sumber inspirasi dalam menulis. Sayangnya, tak banyak seperti itu. Banyak penulis justru terjebak dengan menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari dengan aktivitas di media sosial; membalas setiap komentar pada kiriman miliknya atau kawan lain, yang tak jarang jatuh pada pergunjingan dan debat kusir,. Menghabiskan waktu dan energi yang sebenarnya bisa digunakan untuk hal yang produktif.
Jika hanya 2-5 kiriman di akun pribadi setiap hari, itu masih tergolong normal. Tapi bagaimana jika 10-15? Hal itu hanya menunjukkan sebuah kondisi mental-emosional yang kurang stabil; bisa jadi sedang gelisah, marah, atau sedih dan membutuhkan perhatian dari orang lain sesama pengguna media sosial.
Tapi, bagaimana jika itu menjadi sebuah kebiasaan? Tentu hal tersebut kurang baik, bisa membuat kawan-kawan media sosial menjadi tak nyaman dengan kita. Niat awal berbagi rasa dan pemikiran akhirnya hanya menjadi “gerundelan” bahkan racauan, berasal dari sampah-sampah pikiran yang kita kira menemukan saluran tepat, tapi sayangnya tidak demikian.
Ada baiknya energi kreatif tersebut digunakan untuk menulis buku. Atau, jika dirasa berat, sebuah artikel, esai, cerpen dan puisi. Banyak jenis tulisan yang bisa dipilih. Pun, media konvensional (koran, majalah, tabloid, buletin) atau yang kini menjadi tren, media daring, siap memuat tulisan kita sesuai segmen dan genre pembaca yang beragam. Tulisan yang tersebar di media massa dan juga buku menjadikan aktivitas dan energi kreativitas menjadi tidak sia-sia. Sekadar “berkicau” atau bahkan menceracau di media sosial. (*)
Tentang Penulis
Angga Wijaya, bernama lengkap I Ketut Angga Wijaya lahir di Negara, Bali, 14 Februari 1984. Menulis puisi, esai, karya jurnalistik dan sedang ingin menekuni cerita pendek serta novel. Belajar menulis secara intens sejak SMA saat bergabung dengan Komunitas Kertas Budaya asuhan penyair Nanoq da Kansas di kota kelahirannya. Selain penulis, ia bekerja sebagai wartawan di Denpasar, Bali.